"Pemberontakan" Para Pengarang
“Triyanto Triwikromo, Gus Tf. Sakai, atau Ayu Utami memang berbakat besar sebagai seorang sastrawan!” kata seorang teman suatu ketika. Yup, mereka, yang diberi label sastrawan itu diketahui berbakat setelah dari tangannya meluncur tes-teks sastra masterpiece. Hampir tak ada orang yang bisa menyebutnya seseorang itu memiliki bakat tertentu sebelum mampu membuktikan talentanya.
Saya kurang mempercayai betul adanya bakat. Keyakinan yang terlalu “mendewakan” bakat justru akan menjadi penghambat serius ketika kita sudah berniat mengibarkan bendera imajinasi kita dalam dunia kepenulisan. Tuhan menganugerahi kita dengan potensi-potensi “laten”. Semuanya butuh digali, digarap, dipupuk, dan dikembangkan hingga menjadi sebuah lahan yang subur. Baru menulis beberapa cerpen, tetapi tak satu pun yang bisa terselesaikan, lantas mengklaim dan mengutuk diri sendiri, “Kayaknya aku memang ndak berbakat nih. Bikin cerpen ndak pernah selesai!” Aduh, kenapa bisa berpandangan naif semacam itu, yak? Hehehehehe :lol:
Budi Darma pernah bilang jika Anda belum dikenal sebagai sastrawan, cobalah memberontak. Katakan sastra hasil karya pengarang kita belum berbobot. Kutiplah keterangan dari pengarang dunia kaleber kakap. Atau, tulislah sebuah puisi yang nyentrik. Tentu Anda akan menjadi terkenal mendadak.
Paling tidak, ada dua kandungan tafsir yang tersirat di balik pernyataan pengarang novel Olenka itu. Pertama, sebagai “pasemon” terhadap kelatahan pengarang yang suka bikin sensasi lewat eksperimentasi penciptaan yang mentah dan konyol, tanpa dibarengi akuntabilitas moral dan etik. Artinya, “pemberontakan” hanya dilakukan untuk memburu ketenaran nama an-sich, tidak berbasiskan kultur penciptaan yang dengan sangat sadar dilakukan untuk melahirkan teks-teks kreatif yang bernilai.
Kedua, “pemberontakan” bisa dimaknai sebagai upaya pengarang (baca: sastrawan) dalam melakukan perburuan kreativitas penciptaan yang lebih berbobot, sehingga mampu mengembuskan napas dan arus kesadaran baru lewat teks-teks sastra masterpiece sekaligus menyejarah. Atau lewat” pemberontakan” yang dilakukannya, sang sastrawan sanggup menancapkan tonggak sejarah baru di tengah-tengah dinamika kesusastraan.
Hampir setiap angkatan sejarah mencatat kemunculan para “pemberontak” yang berupaya melakukan pembebasan “mitos” penciptaan teks-teks sastra. “Pemberontakan” yang mereka lakukan bukanlah sikap latah yang berambisi melambungkan namanya di tengah jagat kesusastraan, tetapi lebih berupaya mencari dan menemukan bentuk pengucapan yang sesuai dengan tuntutan hati nurani dan kepekaan estetikanya.
Marah Rusli lewat Siti Nurbaya pada masa Balai Pustaka, Armyn Pane lewat Belenggu pada masa Pujangga Baru, Chairil Anwar lewat sajak “Aku” pada Angkatan ‘45, Sutarji Calzoum Bachri (penyair) lewat antologi O, Amuk, Kapak, atau Danarto lewat antologi Godlob pada era 1970-an adalah beberapa nama yang bisa dibilang sukses melakukan “pemberontakan” kreatif, sehingga bobot kesastraan mereka amat diperhitungkan dalam diskursus sastra kita. Tentu masih banyak pengarang lain yang dengan sangat sadar meniupkan roh dan semangat “pemberontakan” dalam karya-karya mereka.
camus.jpgDalam sastra dunia, konon Albert Camus yang pernah mendapatkan hadiah Nobel Sastra tahun 1957, sebenarnya juga seorang “pemberontak”. Lewat bukunya L’Home Revolte (Manusia Pemberontak), ia mengatakan, manusia perlu memprotes nasibnya. Bahkan, jika perlu ia harus memprotes seluruh makhluk dan kehidupan yang ada di dunia ini sesuai dengan kondisi yang ada (Atmosuwito, 1989). Ini artinya, “pemberontakan” kreatif yang dengan sangat sadar dilakukan oleh seorang sastrawan, baik dalam aspek muatan maupun aspek penyajian, akan mampu menciptakan dan melahirkan teks sastra baru yang inovatif dan “monumental”.
Harus diakui, kesusastraan mutakhir kita baru memiliki beberapa gelintir sastrawan yang dengan sangat sadar melakukan “pemberontakan” kreatif lewat teks-teks sastra yang diluncurkannya, bahkan bisa dibilang miskin “pemberontakan”. Sebut saja Ahmad Tohari, seorang ulama yang sukses mengeksplorasi dunia ronggeng daerah Banyumas lengkap dengan warna lokalnya yang khas –blaka suta dan cablaka–dalam triloginya Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jentera Bianglala. Karyanya bisa “melegenda” lantaran keberaniannya melakukan “pcmberontakan” dengan mengungkap pernik-pernik kehidupan dan kultur sosiologis masyarakat grass-root yang ditabukan bagi kalangan santri.
Darmanto Jatman juga bisa dibilang sastrawan “pemberontak”. Lewat teks-teks puisinya, ia melakukan eksplorasi bahasa yang dipadukan dengan penggalian tema-tema manusia marginal, masyarakat paria, yang tak berdaya menghadapi bayang-bayang “adikuasa”. Demikian juga sastrawan muda Triyanto Triwikromo lewat teks-teks cerpen terornya, baik yang terkumpul dalam Rezim Seks maupun Pintu Tertutup Salju (kumpulan cerpen bersama Herlino Soleman) yang berupaya melakukan eksplorasi tema-tema peradaban yang sakit dengan corak penyajian yang dinilai “nyempal” dari tradisi penciptaan cerpen yang pernah muncul.
Keminiman potensi sastrawan “pemberontak”, disadari atau tidak, telah membikin sastra mutakhir kita menjadi sebuah Indonesia yang tertinggal. Hingga kini belum muncul Ahmad Tohari atau Darmanto Jatman baru yang sanggup meluncurkan teks-teks sastra kreatif yang “menghebohkan” publik dan pencinta sastra. Dalam konteks ini, Ayu Utami lewat novel Saman-nya –yang lahir dari sebuah ajang festival– bisa dikatakan sebuah fenomena. Nama yang selama ini (nyaris) tidak menampakkan gairah penciptaan teks-teks sastra lewat media cetak, tiba-tiba saja sanggup meluncurkan sebuah karya yang dipuji banyak pengamat.
Mengapa dinamika sastra mutakhir kita menjadi demikian stagnan? Selain kemiskinan “pemberontakan” kreatif yang dilakukan oleh para pengarang, menurut hemat saya, ada beberapa asumsi yang bisa dikemukakan. Pertama, negeri ini mungkin bukan ladang yang subur bagi pertumbuhan sastra. Gairah penciptaan dan kreativitas para pengarang memang terus mengalir di berbagai media cetak. Namun, hal ini belum bisa jadi bukti eksisnya kehidupan sastra di negeri ini. Apalagi, tradisi kritik, apresiasi publik, dan penghargaan finansial terhadap dunia kesusastraan masih berada pada aras yang amat rendah. Imbasnya, tidak sedikit sastrawan yang hengkang dari kampung halaman dan mengadu nasib ke kota lain. Jarang –lebih tepat dibilang langka– sastrawan yang benar-benar bisa hidup dari dunia yang digelutinya. Pameran dan peluncuran buku atau pentas dan diskusi sastra pun sepi peminat.
Kedua, kelangkaan penerbit yang memiliki idealisme untuk menggairahkan dan menghidupkan buku-buku sastra. Eksistensi seorang pengarang akan terasa makin “sempurna” bila tangannya telah mampu melahirkan sebuah buku. Namun, mewujudkan impian itu tidak mudah, apalagi penerbit mustahil mau menanggung risiko rugi jika kelak buku sastra yang diterbitkannya tak terjamah konsumen. Kondisi penerbitan yang terlalu berorientasi pada keuntungan itu jelas sangat tidak kondusif bagi idealisme pengarang.
Dan ketiga, mandulnya peran Dewan Kesenian (cq Komite Sastra) dalam memberdayakan kantong-kantong sastra di daerah. Keberadaan Dewan Kesenian tak lebih dari sebuah perpanjangan tangan birokrasi yang mengurus persoalan-persoalan administratif dan pendanaan ketimbang substansi dan esensi kesastraan. Akibatnya, potensi local genius kesusastraan tak bisa berkembang. Aktivitas sastra yang bisa dijadikan sebagai ajang untuk menggairahkan dunia penciptaan teks-teks sastra dan apresiasi publik tak pemah tersentuh. Dialog dan curah pikir kesastraan yang mestinya dilakukan secara serius dan intensif pun jarang dilakukan.
Jika kondisi di atas terus berlanjut, bukan mustahil nasib kesusastraan mutakhir kita makin merana dan tak terurus. Dalam konteks demikian, dibutuhkan kesadaran kolektif semua pihak yang masih memiliki kepedulian untuk menghidupkan dunia sastra kita.
Sebagai kreator, sastrawan dituntut memiliki nyali “pemberontakan” kreatif dalam melakukan perburuan, inovasi, eksplorasi aspek muatan hidup dan aspek penyajian sehingga mampu menancapkan tonggak yang “melegenda” dalam khazanah sastra. Jika proses ini berhasil, penerbit yang memiliki idealisme terhadap persoalan-persoalan budaya dan kemanusiaan pasti akan memburunya. Dimensi hidup dan kehidupan di tengah-tengah masyarakat perlu terus digali dan diangkat ke dalam teks-teks sastra, sehingga mampu memancarkan aura kemanusiaan bagi penikmatnya. Fenomena dan perubahan semesta kehidupan memang akan terus tcrjadi. Dengan kepekaan intuitifnya, sastrawan diharapkan mampu menafsirkan dan menerjemahkan berbagai persoalan mikro dan detil kehidupan menjadi lebih bermakna.
Para calon pengarang hendaknya juga jangan terlalu mempercayai adanya bakat. “Pemberontakan” dengan menampilkan teks-teks baru yang lebih liar dan mencengangkan justru akan lebih bernilai dan bermakna ketimbang berdebat soal ada atau tidaknya bakat kepengarangan. Proses kreatif-lah yang akan lebih menentukan keberhasilan seorang pengarang atau calon pengarang.
Masih banyak persoalan sastra yang belum tergarap secara serius, termasuk upaya meningkatkan apresiasi publik terhadap sastra. Dunia pendidikan sebagai wadah pemberdayaan generasi perlu dijadikan ajang apresiasi dan “pembumian” kesusastraan. Bahkan jika perlu, mesti ada program “sastrawan masuk sekolah” –baik secara rutin maupun insidental– untuk membantu guru-guru sastra yang selama ini dianggap gagal menanamkan apresiasi sastra kepada peserta didiknya. Nah! ***
Guru Bahasa, Sastra, dan KTSP
Persoalannya sekarang, sudah benar-benar dalam kondisi siapkah para guru bahasa menyajikan muatan sastra dalam KTSP itu kepada siswa didik? Sanggupkah para guru bahasa kita memikul peran ganda; sebagai guru bahasa dan sekaligus guru sastra? Mampukah para guru bahasa kita memberikan bekal yang cukup memadai kepada anak-anak negeri ini dalam mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis sastra? Hal ini penting saya kemukakan, sebab selama ini memang tidak ada spesifikasi dalam penyajian materi bahasa dan sastra. Guru bahasa dengan sendirinya harus menjadi guru sastra.
Kalau guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai, jelas tidak ada masalah. Mereka bisa mengajak siswa didiknya untuk “berlayar” menikmati samudra sastra dan estetikanya. Melalui sastra, siswa bisa belajar banyak tentang persoalan hidup dan kehidupan, memperoleh “gizi” batin yang mampu mencerahkan hati nurani, sehingga sanggup menghadapi kompleks dan rumitnya persoalan kehidupan secara arif dan dewasa. Namun, secara jujur mesti diakui, tidak semua guru bahasa memiliki kompetensi sastra yang memadai. Minat dan kecintaan guru bahasa terhadap sastra masih menjadi tanda tanya. Tidak berlebihan jika pengajaran sastra di sekolah cenderung monoton, kaku, bahkan membosankan.
Tidak semua guru bahasa mampu menjadikan sastra sebagai “magnet” yang mampu menarik minat siswa untuk mencintai sastra. Yang lebih memprihatinkan, pengajaran sastra hanya sekadar menghafal nama-nama sastrawan beserta hasil karyanya. Siswa tidak pernah diajak untuk menggumuli dan menikmati teks-teks sastra yang sesungguhnya. Kalau kondisi semacam itu terus berlanjut bukan mustahil peserta didik akan mengidap “rabun” sastra berkepanjangan. Implikasi lebih jauh, dambaan pendidikan untuk melahirkan manusia yang utuh dan paripurna hanya akan menjadi impian belaka.
Kini sudah saatnya dipikirkan pemberdayaan guru bahasa dalam pengertian yang sesungguhnya. Format pemberdayaan guru semacam seminar, lokakarya, penataran, atau diklat yang cenderung formal dan kaku, tampaknya sudah tidak efektif. Forum non-formal semacam bengkel sastra barangkali justru akan lebih efektif. Mereka bisa saling berbagi pengalaman dan berdiskusi. Simulasi pengajaran sastra yang ideal bisa dipraktikkan bersama-sama, sehingga guru bahasa memperoleh gambaran konkret tentang cara menyajikan apresiasi sastra yang sebenarnya kepada siswa.
Guru bahasa menjadi figur sentral dalam menaburkan benih dan menyuburkan apresiasi sastra di kalangan peserta didik. Kalau pengajaran sastra diampu oleh guru yang tepat, imajinasi siswa akan terbawa ke dalam suasana pembelajaran yang dinamis, menarik, kreatif, dan menyenangkan. Sebaliknya, jika pengajaran sastra disajikan oleh guru yang salah, bukan mustahil situasi pembelajaran akan terjebak dalam atmosfer yang kaku, monoton, dan membosankan. Imbasnya, gema apresiasi sastra siswa tidak akan pemah bergeser dari “lagu lama”, terpuruk dan tersaruk-saruk.
Kini, KTSP sudah diluncurkan. Dari sisi muatan materi ajar, KTSP terkesan lebih ramping dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Namun, dari sisi pendalaman materi, KTSP terasa lebih intens dan konkret dalam memberikan bekal kompetensi kepada siswa. Secara eksplisit, KTSP sudah mencantumkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Konsekuensinya, guru harus benar-benar mumpuni dan berkompeten di bidangnya. Jika tidak, kegagalan KTSP sudah menanti, menyusul kegagalan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Demikian juga halnya dengan pengajaran sastra. Guru bahasa yang sekaligus guru sastra jelas dituntut memiliki kompetensi dan talenta sastra yang memadai.
Ada baiknya Depdiknas perlu segera melakukan pemetaan guru bahasa untuk mengetahui guru bahasa yang memiliki kompetensi dan minat di bidang sastra. Merekalah yang kelak diharapkan menjadi guru sastra yang mampu membawa dunia siswa untuk mencintai sastra. Guru bahasa yang nihil talenta dan miskin minat sastranya tidak usah dibebani tugas ganda. Biarkan mereka berkonsentrasi di bidang kebahasaan, sehingga mampu memberikan bekal kompetensi kebahasaan secara memadai. Sebaliknya, biarkan pengajaran sastra diurus oleh guru bahasa yang benar-benar memiliki kompetensi dan minat di bidang sastra. Dengan spesialisasi semacam itu, kompetensi bahasa dan sastra siswa diharapkan bisa berkembang bersama-sama tanpa ada yang dianaktirikan. ***
Kristal Hakikat dalam Cerpen Danarto
Sungguh tak terduga kalau tulisan saya “Menguak Absurditas Cerpen Danarto” (Wawasan Minggu, 26 Juni 1988) yang sekadar selentingan itu mendapatkan respon yang sangat menarik dari Bung Rosa Widyawan RP dengan judul “Tentang Cerpen Danarto: Absurditas Macam Apa?” (Wawasan Minggu, 4 September 1988). Ya, sebuah judul yang bernada retorika, namun justru menggelitik untuk dicarikan bias-bias jawabannya. Dengan munculnya tulisan itu, saya bermaksud mengadakan sambung rasa dengan Bung Rosa. Atau, boleh juga dibilang sebagai hak jawab saya atas pertanyaan yang diluncurkan Bung Rosa.
Dalam tulisan itu, Bung Rosa meragukan sekaligus mempertanyakan sisi absurditas yang membayangi cerpen-cerpen Danarto. Bung Rosa akur jia abusrditas yang dimaksud adalah pemerkosaan terhadap hukum logika, sebab absurditas menimbulkan penafsiran yang luas, baik ditinjau dari segi teologi, filsafat, maupun seni. Kemudian, pada akhir uraian, Bung Rosa juga tidak sependapat dnegan pernyataan saya bahwa Danarto adalah seorang pembaharu dalam dunia cerpen Indonesia mutakhir –saya merujuk pendapat Korrie Layun Rampan dan Rayani Sri Widodo—sebab menurut Bung Rosa, cerita-cerita yang dipaparkan Danarto dalam cerpen-cerpennya sudah demikian akrab dalam gendang telinga pembaca.
Kristal Hakikat
Benar memang yang Bung Rosa katakan bahwa absurditas bisa menimbulkan penafsiran yang luas, baik ditinjau dari segi teologi, filsafat, maupun seni. Namun, perlu juga kita garis bawahi bahwa absurditas yang kita bicarakan adalah absurditas yang membayangi cerpen-cerpen seorang Danarto yang tentu saja batas leingkupnya lebih sempit.
Sebagai penulis yang dilandasi alam pikiran moral panteistis yang meyakini bahwa segala-galanya merupakan penjelmaan Tuhan, Danarto telah menjadi begitu yakin bahwa tokoh-tokoh ciptaannya mampu menerobos dimensi ruang dan waktu yang pada akhirnya menemukan klimaks konfliknya di tengah-tengah pertarungan kehidupan maya di alam fana dengan ucapan: “Melihat wajah Tuhan” seperti kata Rintrik, “Aku bukan hidup dan bukan mati. Akulah kekekalan” seperti teriakan Abimanyu ketika maut menyongsongnya, ataupun “O, Pohon Hayatku”, desah perempuan bunting dengan nikmat setelah babaran.
Momen-momen semacam inilah yang menggiring saya untuk mengatakan bahwa sisi absurditas dalam cerpen Danarto akan menjadi lain persoalannya jika dikaitkan dengan istilah absurditas dalam disiplin ilmu yang mahaluas itu. Sisi absurditas dalam cerpen-cerpen Danarto adalah hanya berfungsi sebagai arus-arus dalam menemukan krital hakikat, seperti kata Rayani Sriwidodo. Semacam prakatarsis melihat wajah Tuhan (1983:154).
Kristal hakikat macam apa? Sebagian besar cerpen Danarto yang bernada absurd nyaris berkaitan dnegan mau. Dalam “Dinding Anak”, misalnya, Bibit dikejar-kejar dan dipermainkan oleh Izrail si Malaikat Maut. Karena menjadi anak emas, maka sang ayah mengadakan tipu muslihat dengan mengganti nama Bibit menjadi Sruni. Namun, ternyata takdir berkehendak lain. Bibit keburu direnggut maut ketika namanya diubah menjadi Sruni. Atau, pada cerpen yang bertitel “!”, di mana sang ayah sebagai kepala keluarga sebuah keluarga modern mendapat serangan jantung yang hebat lantaran ulah anaknya yang badung. Namun, apa yang terjadi? Ketika seluruh anggota keluarga dirundung kesedihan setelah sang ayah dinyatakan mati oleh dokter, sang ayah justru mengalunkan lagu Come Back to Sorento dengan berdiri tegap di atas tempat tidur.
Suasana cerpen “Nostalgia” juga demikian. Ketika ajal menghadang karena dihujani busur-busur panah di sekujur tubuhnya dalam perang Bharatayuda, justru Abimanyu menerimanya dnegan erangan kenikmatan. Abimanyu malah tampak lebih gagah dengan busur-busur panah yang menancap di tubuhnya. Rupanya Bibit, sang ayah, dan Abimanyu yang dijadikan medium Danarto dalam menampilkan suasana absurd sebagai arus menuju kristal hakikat sebagai pengejawantahan dari takdir yang mokal bisa dimuslihati atau diingkari oleh manusia. Dan kristal hakikat yang diburu oleh patron tokoh cerpen Danarto adalah maut sebagai titian menuju penyatuan Tuhan (Manunggaling Kawula-Gusti).
Danarto memang bukanlah kaum eksistensialis Barat yang dengan radikalnya menyerap absurditas sebagai objek peneluran karya-karyanya. Akan tetapi, Danarto adalah seorang penulis yang dengan sangat sadar menjadikan sisi absurditas sebagai medium dalam menemukan kristal hakikat. Oleh sebab itu, Abimanyu akan lain halnya dengan Perken dalam “Royal Way”-nya Andre Malraux dalam menghadapi maut. Kalau Abimayu begitu menikmati songsongan maut. Sonder memberontak, tetapi Perken begitu berang dan memberontak ketika dihadang maut saat bertekad membentuk dan mengepalai sebuah negara Asia nun jauh di tengah rimba belantara Indocina. Ketika Sysiphus dikutuk oleh para dewa lantaran mengetahui rahasia para dewa yang harus mengangkat batu ke puncak gunung selalu gagal dengan peluh cucuran keringat berulangkali, barangkali ini sebagai pengejawantahan Albert Camus dalam menampilkan suasana absurditas yang dengan begitu kejam dan sadis memperlakukan Sysiphus.
Namun, Bibit dalam “Dinding Anak” milik Danarto begitu menurut, bahkan beriang ria dipermainkan oleh malaikat Izrail ketika bergelantungan di pohon yang tinggi menjulang pada malam hari. Sebab, Danarto sudah begitu yakin bahwa Bibit sudah saatnya menghadap Sang Pencipta.
Dalam kumpulan cerpen terbarunya Berhala yang memuat 13 cerpen, Danarto tak banyak mengambil imaji Yunani, Bharatayuda, Injil, maupun animisme Jawa. Tokoh-tokohnya pun kebanyakan berasal dari patron manusia lumrah yang manusiawi yang tak begitu memiliki kekuatan supranatural yang serba gaib seperti pada dua kumpulan cerpennya terdahulu. Danarto tak lagi mencomot tokoh-tokoh semacam Ahasveros, Salome, Kadal, Bekakrak, zat asam, maupun tokoh lain dari epos. Kalau toh itu ada, tokoh-tokoh semacam itu hanya sebagai digresi atau penyimpangan dari fokus cerita yang sebenarnya. Misalnya, tokoh “saya” yang berperan sebagai petrus alias penembak misterius dalam “Pundak yang Begini Sempit” tiba-tiba dilanda kegamangan yang hebat tatkala harus menyergap gali yang sedang berpcaran karena ia ingat Pandu dikutuk oleh kijang lantaran telah dibuhnya selagi sedang bermesraan. Ada juga tokoh malaikat dalam “Dinding Anak” yang senantiasa mempermainkan Bibit di pepohonan yang tinggi menjulang depan rumah.
Masih ada tokoh-tokoh lain yang punya kekuatan super, seperti tokoh ayah dalam “Langit Menganga” yang sanggup memusnahkan wadag manusia menjadi air, Wiwin dalam “Cendera Mata” yang sanggup memproduksi berpintal-pintal benang halus dari air matanya, tokoh Kyai dalam “Pageblug” yang sanggup menciptakan sebungkah es meluncur untuk memberantas pageblug, tetapi disalahpahami oleh para penjudi buntut dengan selalu mengejar bungkusan es yang terus meluncur itu. Namun, semuanya hanyalah digresi khas Danarto yang mengklaim tokoh-tokohnya denga kekuatan lebih.
Bukan Pembaharu Tema
Benar yang Bung Rosa katakan bahwa cerita-cerita yang dipaparkan Danarto dalam crpen-cerpennya sudah demikian akrab dalam telinga kita, bahkan cerita-cerita semacam itu telah mbalung sumsum dan bernaung turba (meminjam istilah Rama Mangun) sejak zaman baheula. Akan tetapi, cerita itu hanya berlangsung dari mulut ke mulut secara lisan. Seandainya cerita semacam itu ada dalam bentuk tulis, barangkali belum maujud dalam bentuk cerpen seperti yang Bung Rosa contohkan dalam sekar “Dandang Gula” itu.
Barangkali yang ingin Bung Rosa katakan adalah bukan hal yang baru dari segi tema. Ini benar. Dan saya yakin Danarto bukanlah seorang pembaharu tema dalam khazanah cerpen Indonesia, sebab tema-tema yang disajikannya sudah tidak asing lagi bagi pembaca. Akan tetapi, ada beberapa segi yang terasa baru dalam khazanah cerpen Indonesia yang belu pernah dilakukan dan dimiliki oleh penulis-penulis sebelumnya.
Rayani Sriwidodo pernah menyatakan bahwa ada dua aspek yang menunjukkan corak baru dalam cerpen Danarto, yakni aspek penyajian yang memasukkan unsur puisi, musik, dan seni lukis dalam cerpen-cerpennya sehingga tampak efek puitis, musikal, dan artistik dekoratif, serta aspek muatan yang, yakni adanya tendensi moral patenistis yang meyakini ajaran bahwa segala-galanya merupakan penjelmaan Tuhan. Selain itu, jika kita membaca cerpen-cerpen Danarto akan tampak bahwa sebagian unsur intrinsik dan ekstrinsik banyak menampilakn corak baru. Dari unsur intrinsik, misalnya, corak baru tersebut terletak pada tokoh dan perwatakannya, alur/plot, dan setting.
Tokoh dalam cerpen Danarto adalah tokoh imajiner yang sanggup menerobos terhadap benturan dimensi ruang dan waktu, manusia super yang mampu bertahan dalam situasi dan kondisi apa pun. Hal ini tampak pada “Pundak yang Begini Sempit” yang menceritakan kegelisahan seorang petrus yang dalam setiap tugasnya senantiasa diikuti oleh makhluk berkerudung, bersayap, dan bermata banyak di sekujur tubuhnya yang dengan mudahnya menghilang kapan dan di mana saja. Atau, pada cerpen “Kecubung Pengasihan”, seorang perempuan bunting sanggup bertahan hidup hanya memakan kembang-kembang di taman. Dan masih banyak tokoh lain semacam itu dalam cerpen-cerpen Danarto yang berjumlah 28 judul dari tiga buku kumpulan cerpen tersebut. Pada alur, cerpen Danarto penuh dadakan, kejutan, dan surprise yang sulit diterapkan dengan model alur konvensional. Ending cerita bisa di awal, di tengah, atau di akhir, bahkan ada juga cerita yang tanpa akhir (never ending story).
Dari unsur ekstrinsik –usnur-unsur dari luar cerita yang turut mewarnai suasana cerita—juga menunjukkan corak baru, misalnya tendensi moral panteistis, doktrin sufi yang mengacu pada ajaran wahdat al-wujud serta visi lain dalam benak Danarto dalam memandang dunia.
Untuk mengakhiri sambung rasa ini, perkenankanlah saya mengutip salah sebuah monolog seorang perempuan bunting dalam “Kecubung Pengasihan” ketika melihat kulit rahimnya kian mengembang:
“O, rahim semesta. Demikian agungkah Engkau? Rahimku mengandung diriku sendiri, di manak aku bermain-main di dalamnya dengan tenteramnya.”
ABSURDITAS DALAM CERPEN DANARTO
Sebuah cerpen yang baik –setidak-tidaknya menurut persepsi saya—bukanlah produk mentah yang menghidangkan sajian-sajian vulgar, tetapi butuh proses renungan dan pengendapan setelah melalui pergulatan visi, filosofi, dan latar sosio-kultural yang menggelisahkan mata batin pengarang. Bagaimanapun juga sebuah cerpen tak pernah tercipta dalam kekosongan. Artinya, cerpen akan selalu diwarnai oleh worldview (pandangan dunia) dan pretensi pengarang dalam menangkap fenomena-fenomena sosiokultural yang menggelisahkannya. Beranjak dari sisi ini kejujuran Danarto tersebut justru harus dimaknai sebagai tuntutan komitmen seorang sastrawan yang mau tidak mau harus memiliki doktrin moral-force dan jangan dipersepsikan sebagai kreator yang kekeringan objek imajinatif, impresif, dan cuatan ekspresi.
Seorang Pembaharu
Dalam salah satu esainya, Korrie Layun Rampan pernah mengatakan, Danarto adalah seorang pembaharu dalam khasanah sastra Indonesia. Seorang pembaharu yang sadar, bukan kerena eksperimentasi yang mentah dan konyol. (via Eneste, 1983:146). Aset Danarto sebagai pembaharu bukanlah sebuah slogan. Cerpen-cerpennya menunjukkan kebaruan unik yang berbeda dnegan cerpen-cerpen yang pernah ada. Kebaruan tersebut dapat dilihat dari aspek penyajian dan aspek muatan dalam cerpen-cerpennya. Dari aspek penyajian tampak corak penampilan unsur-unsur puisi, musik dan seni lukis, sehingga mampu memberikan efek puitis, musikal, dan artistik-dekoratif, sampai-sampai pembunuhan yang tragis menjadi begitu indah, ceceran darah menjadi adonan yang begitu manis. Dari aspek muatan. Tampak adanya tendensi moral pantheisme, yakni ajaran yang meyakini doktrin segala-galanya merupakan penjelmaan Tuhan (Rayani Sriwidodo, 1983:147-150). Fenomena-fenomena semacam inilah yang menggiring kita untuk sependapat dengan ucapan Korrie Layun Rampan.
Predikat sebagai pembaharu agaknya juga disepakati oleh Umar Kayam yang menyatakan bahwa di Indonesia belum ada seorang penulis cerpen yang dengan sangat sadar menciptakan dunia laternatif dalam cerita-ceritanya, kecuali Danarto. Dua kumpulan cerpen jelas menunjukkan adanya dunai alternatif yang dengan senantiasa mengajak pembaca untuk memasuki sebuah dunia yang bukan milik orang awam. Pembaca dihadapkan pada sbeuah misteri yang tak pernah tuntas, teror, kebrutalan, dan sekian perbuatan superior yang tidak kepalang tanggung. Cerpen Danarto hanyalah memberikan arah saja seperti yang dikatakan Iwan Simatupang (via Eneste, 1983:346) bahwa pengarang cerpen hanyalah memberi arah saja. Danarto lewat cerpen-cerpennya memberikan prelogika yang harus dilogikakan sendiri oleh pembaca sehingga mampu mengundang berbagai alternatif interpretasi. Cerpen yang mengandung kekuatan teror mental yang mahadahsyat.
Pada kumpulan cerpen terbarunya, Berhala, Danarto mencuat dengan gebrakan baru. Saya katakan demikian, sebab persepsinya terdahulu nyaris ditinggalkannya. Dunia alternatif –yang menjadi karakteristik pada kumpulan cerpennya terdahulu- bergeser ke dunia realitas yang manusiawi. Danarto tak lagi berbicara tentang dunia sonya-ruri yang penuh ambigu—meski tidak semuanya—tetapi lebih gelisah pada masalah-masalah sosial yang menghinggapi manusia-manusia metropolis. Keterlibatan tokoh “saya” nyaris menjadi ajang pembredelan borok-borok manusia metropolis. Danarto menjadi peka terhadap problem-problem sosial manusia kapitalis yang cenderung mekanis dan memola manusia untuk menghamba pada kepuasan hedonis. Barangkali Danarto telah punya pandangan lain tentang sastra yang tidak harus melulu mengabdi pada kepentingan susastra, tretapi bisa dijadikan sebagai medium untuk mencuatkan obsesi kegelisahan terhadap kenyataan sosial yang korup. Apakah ini pertanda terbuktinya konsepsi Satyagraha Hurip tentang Sastra Terlibat di mana sastra harus turut memperbaiki moral bangsa?
Doktrin Sufi
Walaupun cerpen Danarto berbicara masalah sosial, agaknya tradisi yang khas yang tak mungkin bisa ditinggalkannya, takni suasana absurditas. Bukanlah Danarto kalau tidak memasukkan suasana absurd dalam cerpen-cerpennya.
Sebagai seorang Jawa Isalam yang taat dan dibesarkan di lingkunagn budaya Jawa Tengah (Sragen, Solo, dan Yogya), Danarto terpelanting pada dunia tassawuf, dunia kaum sufi yang bersiteguh pada doktrin wahdat al-wujud (ketunggalan wujud atau ketunggalan kehadiran) di mana semua pernyataan keheidupan menemukan ke-Esa-annya kepada Sang pencipta (Umar Kayam, 1987). Hal ini sesuai dengan pernyataannya bahwa kita ini adalah milik Sang pencipta secara absolut dan ditentukan (Danarto, 1983). Oleh sebab itu, tidak terlalu mengherankan jika hampir semua cerpennya selalu dinapasi doktrin sufi yang begitu akrab bergelayut dalam perjalanan hidupnya.
Namun begitu, cerpen-cerpennya bukanlah cerpen vulgar yang hanya mengaplikasikan doktrin sufi secara mentah, tetapi melalui pencerapan yang diadopsikan dengan bias-bias realita yang berhasil ditangkap melalui syaraf intuitifnya. Tampaklah bahwa cerpennya bukan sekadar mengobral doktrin mentah seperti orang berkhotbah.
Rayani Sriwidodo pernah menyinyalir bahwa Danarto juga terpengaruh oleh bayangan absurditas yang dianut oleh kaum eksistensialis pemikir Barat yang berdasar pada keyakinan bahwa manusia berada dalam satu dunia irasional yang tanpa arti. Hanya bedanya, Danarto lebih mengandalkan intuisi daripada rasio. Tradisi berpikir sistematis belum menjadi miliknya. Sedangkan, kaum eksistensialis Barat bertolak dari rasio yang menuntunnya ke arah sistem filsafat atau setidaknya kecenderungan falsafi yang jelas penalran ilmiahnya. Namun, agaknya semua itu di-nonsens-kan oleh Danarto yang lebih meyakini adanya proses dalam lingkaran kreasinya.
Tak pelak lagi, doktrin sufi sebagai salah satu corak agamawi berhasil menggiring Danarto untuk menghasilkan karya sastra yang transenden. Kepekaan akan kesadaran religius yang diproses melalui tatapan mata batinnya yang sensitif dalam mencuatkan obsesi kegelisahannya. Doktrin The Merging of Servant and Master (Manunggaling Kawula-Gusti) yang merupakan pancaran wahdat al-wujud senantiasa menjadi titik sentral dengan penggarapannya yang fantastis dan teatral. Hal ini tampak sekali pada salah satu cerpennya “Anakmu Bukanlah Anakmu, ujar Gibran” di mana Niken hamil tanpa seorang lelaki pun yang menjamahnya, meski pada akhirnya Niken menikah dengan pemuda Tomo yang papa dan tak dikenalnya. Anehnya, pada pesta perkawinannya muncul Khalil Gibran –seorang tokoh sufi yang telah meninggal tahun 1931—datang memberikan kado. Atau, pada cerpen “Bulan Sepotong Semangka” (Kompas, 12 Juni 1988), tokoh Nari juga hamil tanpa seorang lelaki pun yang menyentuhnya. Tanpa sesal. Bahkan, Nari bagaikan seorang resi yang bertapa di kamar abadinya. Tanpa makan dan minum sampai akhirnya ia melahirkan, bahkan sampai anaknya, Bim, dewasa, kuliah di Fisipol di universitas kamar abadinya dengan dosesnnya Nari sendiri. Fantastis! Niken ataupu Nari rupanya dijadikan tumpuan Danarto untuk mencuatkan doktrin sufinya. Betapapun masalah yang digarap sederhana, Danarto tak mungkin bisa meninggalkan suasana absurd dalam cerpen-cerpennya yang fantastis dan teatral. Tradisi kreativitas yang telah mengikatnya erat-erat tak mungkin ditinggalkannya. Danarto telah punya tradisi kepenulisan yang khas.
Untuk memahami cerpen-cerpen Danarto secara otentik, paling tidak kita harus menelusuri doktrin sufinya yang liat dan kental dalam perjalanan hidupnya. Selain itu, kita harus meohoknya dari latar sosiokultural yang melingkupinya. Tanpa tohokan semacam itu kita hanya akan dihadapkan pada cerpen abstrak yang sulit untuk dimaknai. ***
Memburu Legitimasi lewat Antologi Sastra
Sebaliknya, mereka yang belum memiliki antologi, meski sudah bertahun-tahun intens menggeluti dunia kesastraan, belum layak menyandang predikat sastrawan.
Antologi memang bisa menjadi alat dan media mengukuhkan legitimasi kesastrawanan seseorang. Apalagi, seseorang yang memilih dunia kesastraan sebagai bagian dari ”panggilan” hidup tetaplah butuh pengakuan.
Kehadiran sebuah antologi bisa jadi akan makin mengukuhkannya sebagai sastrawan. Namun persoalan akan menjadi lain ketika antologi menjadi sekadar tujuan.
Menggeluti dunia sastra hakikatnya memahami hidup dan kehidupan sebagai bagian dari dinamika kebudayaan yang berujung pada upaya pemuliaan hidup dan martabat kemanusiaan. Teks-teks kreatif yang lahir dari tangan sastrawan mesti dipahami sebagai perwujudan dan pengejawantahan ”kebajikan” hidup untuk memberikan penafsiran dan penerjemahan kompleksitas denyut kehidupan, sehingga memberikan ”katarsis” dan pencerahan hidup dari berbagai macam pembonsaian nilai-nilai kemanusiaan.
Karena menggeluti dunia sastra adalah panggilan hidup untuk memuliakan nilai dan martabat kemanusiaan, kreativitas sastrawan akan senantiasa diuji oleh zaman dan dinamika peradaban. Artinya, kematangan dan kedewasaan kreativitas seorang sastrawan tidak semata-mata ditentukan oleh kehadiran sebuah antologi, tetapi lebih oleh gairah dan kesuntukan menggeluti kesastraan sebagai panggilan hidup.
Kalau toh hadir sebuah antologi yang menampung teks-teks kreatifnya, itu mesti dimaknai sebagai imbas, efek samping, atau bolehlah disebut ”tonggak sejarah” yang benar-benar melegitimasi derajat kesastrawanannya.
Persoalannya, hidup di tengah-tengah zaman yang kian kapitalistis seperti saat ini tidaklah mudah mendapatkan penerbit yang benar-benar memiliki idealisme untuk menerbitkan antologi sastra. Untung-rugi selalu menjadi pertimbangan utama. Sebuah penerbit tidak akan berbuat konyol dengan menerbitkan buku-buku sastra (termasuk antologi) kalau akhirnya buku-buku itu tidak laku.
Ya, para penulis memang masih bisa berkiprah meluncurkan teks kreatif melalui media massa. Namun, umumnya, hanya singgah sebentar dalam imaji publik, tidak semua mampu ”memfosil” dan menyejarah dalam wilayah apresiasi. Hanya beberapa di antara mereka mampu membangun kolaborasi dengan penerbit, sehingga punya antologi.
Lantas, bagaimana dengan karya-karya penulis yang secara literer tidak kalah hebat dari teks-teks sastra yang terantologi, namun tak terjamah penerbit buku?
Dalam konteks itu, mungkin dibutuhkan kehadiran seorang dokumentator dan kritikus sastra sekelas almarhum HB Jassin yang dengan cermat, suntuk, dan intens senantiasa mengikuti perkembangan dan dinamika teks sastra yang terpublikasikan di berbagai media massa, untuk selanjutnya membedah dan menganalisis tanpa harus menggunakan perangkat teori sastra yang muluk-muluk dan bombastis.
Sayang, selain Korrie Layun Rampan yang memproklamasikan Angkatan 2000 dengan segenap kelebihan dan kekurangannya, kehadiran HB Jassin ”baru” dalam kesastraan kita tetap tanda tanya besar.
Dan, gairah kreativitas penulisan teks-teks sastra yang gencar mengalir dalam bentuk antologi tanpa diimbangi kesuntukan dan intensitas kritik sastra yang memadai hanya akan melahirkan kelatahan dan kekenesan. ***
Kreativitas Penciptaan: antara Kekuatan Personal dan Atmosfer Komunitas









 Ya, ya, ya! Kalau kita mengikuti alur sejarah, seorang penulis besar memang dilahirkan oleh zamannya. Almarhum Pram, misalnya, dia menjadi besar justru karena mengalami berbagai peristiwa kelam yang sarat dengan penindasan dan tekanan. Perpaduan atmosfer represif yang terus menderanya, ditopang minat besar dan semangat perlawanan yang luar biasa, diakui atau tidak, telah membawanya pada suasana kreativitas yang menggelora dan membadai dalam kepekaan imajinasinya. Dalam suasana tertekan, Pram justru terpacu untuk memburu jatidiri lewat jalan pena yang bertahun-tahun digelutinya. Namun, sebelum melahirkan karya-karya masterpiece, adakah orang yang berani menjamin kalau Pram memang memiliki bakat dan talenta menulis? Bisakah diketahui dengan pasti bahwa si Polan adalah seseorang yang punya bakat besar di bidang kepenulisan sebelum melahirkan teks-teks kreatif yang meluncur dari tangannya?
Ya, ya, ya! Kalau kita mengikuti alur sejarah, seorang penulis besar memang dilahirkan oleh zamannya. Almarhum Pram, misalnya, dia menjadi besar justru karena mengalami berbagai peristiwa kelam yang sarat dengan penindasan dan tekanan. Perpaduan atmosfer represif yang terus menderanya, ditopang minat besar dan semangat perlawanan yang luar biasa, diakui atau tidak, telah membawanya pada suasana kreativitas yang menggelora dan membadai dalam kepekaan imajinasinya. Dalam suasana tertekan, Pram justru terpacu untuk memburu jatidiri lewat jalan pena yang bertahun-tahun digelutinya. Namun, sebelum melahirkan karya-karya masterpiece, adakah orang yang berani menjamin kalau Pram memang memiliki bakat dan talenta menulis? Bisakah diketahui dengan pasti bahwa si Polan adalah seseorang yang punya bakat besar di bidang kepenulisan sebelum melahirkan teks-teks kreatif yang meluncur dari tangannya?Bisa jadi memang ada pengaruh bakat atau talenta sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir ketika seorang penulis menyandang nama besar. Namun, mereka diyakini tak lahir begitu saja sebagai seorang penulis, tetapi melalui sebuah proses. Bahkan, bukan mustahil bakat itu jadi sia-sia kalau tak diasah, dipertajam, atau dikembangkan lebih lanjut. Yang justru akan menjadi kendali seorang penulis adalah minat dan semangat besar, ditopang dengan ketekunan untuk mengasah kemampuan dan menggali potensi diri hingga talenta itu benar-benar mencuat ke permukaan. Pengalaman literer dinilai juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap serajat kepengarangan seseorang. Secara otodidak, mereka mencoba mengakrabi berbagai bacaan berbobot literer tertentu sehingga secara tidak langsung menempa kepekaan intuitifnya atau mengembangkan daya jelajah imajinatifnya.
Yang tidak kalah penting, jelas atmosfer kreativitas yang mendukungnya. Atmosfer kreativitas tak selalu identik dengan suasana kemanjaan dan kemerdekaan berkreasi. Situasi yang serba tertindas dan tertekan bisa juga dimaknai sebagai sebuah atmosfer kreativitas yang bisa mendorong seseorang untuk terus berkarya sebagai upaya untuk mendapatkan legitimasi kepenulisan di tengah deraan nasib yang menelikungnya.
Dalam konteks demikian, betapa perlunya menciptakan atmosfer kreativitas sebagai media untuk membangun ruang-ruang berkreasi, khususnya bagi calon-calon penulis. Mereka butuh banyak asupan kreativitas dari orang-orang sekelilingnya untuk memacu semangat dan “adrenalin”-nya dalam mengasah potensi yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, lahirnya kantong-kantong dan komunitas-komunitas sastra bisa dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan atmosfer kreativitas itu; bukan lantaran sikap latah, apalagi sikap berkenes ria. Dengan kata lain, kehadiran kantong dan komunitas sastra bukan dimaksudkan untuk menggiring sang penulis ke dalam ideologi atau ikatan primordial tertentu. Sebagai sosok yang merdeka dan otonom, sang penulis tetap memiliki kekuatan personal untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter dan kekhasan dirinya.
Dalam sebuah obrolan dengan penulis pemula, saya digelisahkan oleh lontaran pendapatnya yang cukup menggelitik untuk dicermati.
“Waktu di SMP dan SMA saya merasa kesulitan menemukan tempat yang nyaman, yang bisa memacu saya untuk belajar menulis. Rata-rata, orang di sekeliling saya cuek dan tak peduli. Saya sangat merindukan sebuah pertemuan yang bisa memberikan saran dan kritik terhadap tulisan-tulisan saya. Namun, selama ini saya belum menemukannya, hingga akhirnya setelah saya bekerja, saya berpendapat bahwa saya memang tak berbakat menjadi seorang penulis!”
Dari nada bicaranya, saya menangkap kesan kuat betapa seorang calon penulis, sebut saja Wulan, amat membutuhkan atmosfer sebuah komunitas yang bisa terus mengasah kepekaan intuisi dan imajinasinya. Memang benar, selama ini seorang pengarang dengan kekuatan personalnya bisa melahirkan karya-karya besar, tanpa harus melalui jalan komunitas. Melalui pengalaman-pengalaman literer dan semangat besarnya, mereka bisa eksis berkreasi hingga tak jarang sanggup melahirkan karya masterpiece. Namun, sungguh, alangkah naifnya apabila kita gagal menyediakan sebuah komunitas yang nyaman buat calon-calon penulis akibat keasyikan kita memburu jatidiri. ***
Kekuasaan dan Seks dalam Novel Belantik
Harus diakui, Ahmad Tohari terbilang sastrawan yang cukup produktif. Novel triloginya, Ronggeng Dukuh Paruk, Jentera Bianglala, dan Lintang Kemukus Dini Hari telah diterbitkan ke dalam berbagai bahasa. Apa sebenarnya yang menarik dari teks-teks kreatif Kang Tohari, sehingga mampu “menyihir” imajinasi banyak kalangan?
 Dalam penafsiran awam saya, setidaknya sastrawan kelahiran Tinggarjaya, Jatilawang, Purwokerto, Jawa Tengah itu, memiliki tiga kekuatan. Pertama, memiliki gaya bertutur yang jernih, lincah, lugas, cablaka, dan bersahaja dalam meluncurkan ide-ide kreatif. Dia tak mau bertele-tele dengan menggunakan gaya metafor yang mbulet dan membikin kening pembaca berkerut.
Dalam penafsiran awam saya, setidaknya sastrawan kelahiran Tinggarjaya, Jatilawang, Purwokerto, Jawa Tengah itu, memiliki tiga kekuatan. Pertama, memiliki gaya bertutur yang jernih, lincah, lugas, cablaka, dan bersahaja dalam meluncurkan ide-ide kreatif. Dia tak mau bertele-tele dengan menggunakan gaya metafor yang mbulet dan membikin kening pembaca berkerut.
Kedua, gigih menyuarakan derita kaum tertindas di tengah hegemoni penguasa yang serakah, hipokrit, dan ambisius. Tanpa kesan menggurui, dia mampu menggiring pembaca berempati terhadap kehidupan kaum paria yang penuh air mata, luka, dan darah.
Ketiga, konsisten mengangkat dunia santri dan budaya Jawa yang diyakini dapat menjadi “roh” kehidupan hakiki di tengah gerusan modernisasi yang mengglobal dan kosmopolitan. Berangkat dari keakraban pada dunia santri dan filsafat Jawa, lewat patron tokoh-tokohnya, Kang Tohari –meminjam istilah Bakdi Sumanto—tapa ngrame. Dia mengembara dalam atmosfer kehidupan yang makin licik; licin, melingkar, sekaligus menjerat.
***
 Salah satu novel yang menarik bagi saya adalah Belantik yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama (2001). Dalam novel setebal 142 halaman ini, Kang Tohari “menghidupkan” tokoh Lasi. Perempuan kampung Karangsoga yang cantik, eksotis, dan menggairahkan mata lelaki itu gagal membangun rumah tangga karena dikhianati Darsa, sang suami. Lasi menumpang truk pengangkut gula aren dan terdampar di Jakarta yang menaburka bau kemewahan.
Salah satu novel yang menarik bagi saya adalah Belantik yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama (2001). Dalam novel setebal 142 halaman ini, Kang Tohari “menghidupkan” tokoh Lasi. Perempuan kampung Karangsoga yang cantik, eksotis, dan menggairahkan mata lelaki itu gagal membangun rumah tangga karena dikhianati Darsa, sang suami. Lasi menumpang truk pengangkut gula aren dan terdampar di Jakarta yang menaburka bau kemewahan.
Lasi yang cantik dan menggiurkan, menggerakkan naluri bisnis Bu Lanting, mucikari kelas kakap. Dia pun jatuh ke dalam pelukan Handarbeni, lelaki tua kaya raya, tetapi impoten. Lasi hidup di tengah kemanjaan dan gelimang kemewahan, tetapi tidak bahagia. Dia justru gelisah dan kesepian.
Lepas dari Handarbeni, Lasi jatuh dalam cengkeraman Bambung, lelaki berdaya berahi dan pengaruh luar biasa, pelobi ulung, broker politik dan kekuasaan. Bambung cukup disegani kalangan politisi, pejabat, dan konglomerat. Hampir semua proyek besar di Indonesia tak pernah luput dari tangannya. Namun, dengan segenap kepolosannya, Lasi masih mampu mempertahankan kesuciannya.
Daya pikat Jakarta, kota metropolitan yang diserbu kaum urban, tak sanggup membuat Lasi melupakan ketenteraman dan ketenangan Karangsoga, kampung kelahirannya. Dia belum bisa melupakan Darsa. Kepada lelaki itulah dia pernah menghadirkan keutuhan diri sebagai istri sempurna. Sayang, Darsa berkhianat; menghamili gadis sekampung.
Lasi juga teringat Kanjat. Lelaki teman sepermainan waktu kecil yang kini menjadi dosen itu diam-diam bersemayam di hatinya. Lain saat, wajah Mak Wiryaji, emaknya yang jujur dan sederhana, tampil dalam layar benaknya. Demikian juga Eyang Mus, imam surau yang selalu suntuk menyiramkan kesejukan ajaran Illahi.
Kerinduan itu membuat Lasi nekad kabur dari cengkeraman Jakarta. Tiba di Karangsoga, Lasi kembali menemukan dunianya. Apalagi, Kanjat masih seperti dulu; ramah dan penuh pengertian. Namun, Lasi masih dihantui bayangan Bu Lanting dan Bambung. Entah kenapa, seperti mampu menangkap geliat batinnya, Eyang Mus yang arif mengawinkan Lasi dan kanjat secara syariat; sah secara agama, tetapi belum sah secara hukum.
Rupanya permainan belum berakhir. Bambung terus memburu bekisar merah, sebutan bagi perempuan cantik seperti Lasi, miliknya yang kabur. Lewat tangan Bu Lanting dan aparat kepolisian, Bambung “menerbangkan” Lasi kembali ke Jakarta. Seiring dengan itu, Kejaksaan Agung gencar mengusut kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang diduga melibatkan para pejabat dan orang penting. Bambung termasuk salah seorang koruptor yang diincar. Lasi pun diperiksa sebagai saksi.
Kasus yang gencar diberitakan berbagai media massa itu membuat Kanjat merasa perlu menyelamatkan sang istri. Setelah diperiksa secara maraton, Lasi dinyatakan bebas dan bisa kembali ke Karangsoga bersama Kanjat.
***
Secara tematis, novel ini mampu menghadirkan intrik seks dalam lingkaran kekuasaan belantik politik dan kekuasaan; memikat dan menghanyutkan. Lewat gaya ucapnya yang khas, Kang Tohari mampu menumbuhkan empati pembaca terhadap nasib kehidupan Lasi, sekaligus mengutuk perilaku si bebek Manila, Bu Lanting, dan si bajul buntung, Bambung, yang korup, ambisius, dan serakah.
Seperti dalam novel-novel sebelumnya, Kang Tohari menghadirkan “kolaborasi” antara dunia santri dan budaya Jawa sebagai dasar falsafi dalam memahami arus utama peradaban yang makin kapitalistis, konsumtif, dan hedonis. Tak luput, secara pedas dia mengkritik klaim keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya menyengsarakan dan membodohi rakyat.
Simak saja penuturan berikut ini!
… Namun bersamaan denga itu berlangsung pembusukan moral berupa pengingkaran terhadap asas-asas bernegara republik serta meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme ….. Lebih jauh orang bilang, kemajuan yang sering diklaim sebagai hasil usaha pemerintah sesungguhnya hanya sehelai kertas yang menutupi borok-borok besar di bawahnya … Dan, Lasi hanyalah satu di antara hamoir 170 juta manusia yang tidak akan pernah pengerti permainan tingkat tinggi di Indonesia. (hal. 43)
Alhasil, novel ini setidaknya mampu memberikan “katharsis” dan pencerahan kepada pembaca, yakni untuk mendengarkan kejernihan suara hati dalam memahami fenomena hidup dan kehidupan yang makin amburadul oleh “pedang” kekuasaan. Dalam dunia seperti itulah banyak “belantik” bermain mengambil keuntungan. ***
Menggapai Makna Kearifan Hidup lewat Sastra
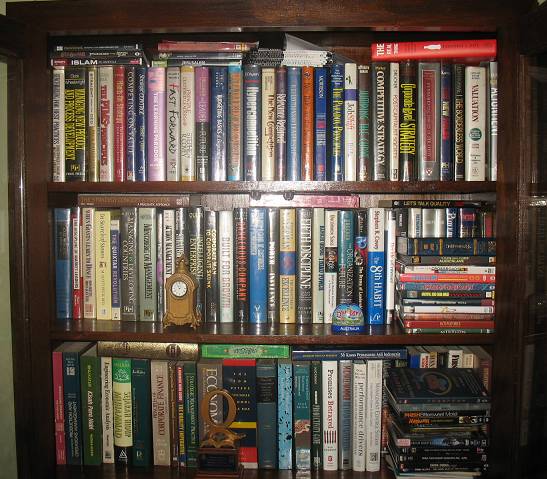 Cerita rekaan yang penulis maksud adalah cerita rekaan yang ditulis berdasarkan khayalan, tetapi mengandung nilai-nilai sastra. Sednagkan, cerita rekaan yang digarap secara vulgar (kasar) tanpa mempertimbangkan bobot sastranya tidak termasuk dalam lingkup pembicaraan ini.
Cerita rekaan yang penulis maksud adalah cerita rekaan yang ditulis berdasarkan khayalan, tetapi mengandung nilai-nilai sastra. Sednagkan, cerita rekaan yang digarap secara vulgar (kasar) tanpa mempertimbangkan bobot sastranya tidak termasuk dalam lingkup pembicaraan ini.Seperti yang diungkapkan Rene Wellek dan Austin Warren dalam bukunya “Theory of Literature” (New York: 1956), sebuah cerita rekaan akan mengandung nilai-nilai sastra jika memenuhi ciri-ciri: fiction (rekaan), imagination (daya angan), dan invenstion (penemuan). Dengan demikian, jika ada salah satu unsur ciri yang tidak digarap, maka cerita tersebut tidak memiliki bobot ditilik dari kansungan nilai-nilai sastranya.
Benarkah dengan banyakn membaca cerita rekaan batin seorang pembaca semakin kaya? Nah, untuk menjawabnya, mari kita mencoba melacaknya dari sudut pandang eksistensi penulis, cerita rekaan, dan publik (pembaca). Sebab, menurut pemahaman penulis, ketiga elemen tersebut membentuk satu keterkaitan yang padu sehingga membentuk satu sistem yang mokal dapat dipisahkan eksitensinya.
Seorang penulis mustahil berproses kreatif tanpa ada tendensi tertentu yang ingin dicapai lewat karyanya. Penulis memiliki semacam komitmen moral untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang buram. Nah, komitmen mereka kemudian disalurkan lewat media tulisan. Dari tulisan inilah akhirnya pembaca dapat menangkap visi pengarang dalam memandang dunia, latar sosiokultural, dan sejumlah pengalaman lain yang digunakan untuk membangun cerita sehingga muncul rasa kekaguman dan simpatik terhadap sang pengarang.
Pembaca melalui daya serapnya akan memberikan nilai lebih kepada pengarang yang benar-benar memiliki komitmen moral dalam upaya mengentaskan kondisi masyarakat yang buram melalui persoalan-persoalan yang digarap melalui ceritanya. Dengan demikian, batin pembaca akan tersusupi oleh gagasan, pendapat, sikap, dan keyakinan penulisnya yang secara sugestif mampu meluruskan sikap hidup pembaca yang nglempuruk sekaligus dapat menghindari segala rangsang hedonis yang cenderung memburu kepuasan ragawi.
Cerita Rekaan
Melalui cerita rekaan yang telah berhasil disuguhkan sang pengarang, pembaca dapat mengidentifikasikan dirinya dengan bebas terhadap tokoh-tokoh dalam cerita sehingga pembaca memperoleh sentuhan manusiawi untuk menyiasati kehidupan yang kian pengap ini.
Kadang kala pembaca dibuat terpukau oleh lukisan-lukisan tokoh cerita yang amat majemuk jenisnya. Kemudian, pembaca berupaya untuk meneladani tokoh cerita yang berwatak manusiawi, lemah tetapi memiliki nilai lebih.
Selain itu, pembaca dapat menikmati adegan-adegan tertulis yang dapat menerbangkan alam pikirannya terhadap hal-hal yang tak mungkin dijangkau dengan pancainderanya. Dengan membaca buku “Catatan Harian” karangan Anne Frank, misalnya, batin pembaca diajak untuk menyiasati suka-deuka sebuah keluarga Yahudi yang terpaksa menyembunyikan diri di atas loteng sebuah rumah waktu pendudukan Jerman. Atau, pada saat membaca cerpen “Kisah Sebuah Celana Pendek”-nya Idrus, batin pembaca diajak untuk menyusupi lorong kehidupan wong cilik yang harus bergulat dengan kesengsaraan yang mencekiknya pada saat Jepang berkuasa setelah pecahnya Perang Pasifik tahun 1941. Orang-orang gehean mencurahkan perhatiannya pada persoalan politik, tetapi wong cilik harus meratapi nasibnya karena kelaparan. Dan, masih banyak cerita-cerita rekaan lain sanggup menyuburkan sikap humani pembaca dalam mengimbangi arus teknostruktur yang kian menggila.
Melalui bahasa dan pengolahan bahan dalam cerita rekaan, mata batin pembaca akan terbuka untuk menerima pengalaman-pengalaman baru yang begitu kompleks. Bahasa dalam cerita rekaan adalah bahasa bebas, bahkan dengan bebasnya pengarang berupaya untuk tidak terbelenggu oleh benturan dimensi ruang dan waktu sehingga sanggup mengekspresikan perasaannya dengan sejelas-jelasnya kepada pembaca.
Bahan yang diolah pengarang pada umumnya adalah persoalan yang aktual, menarik, merangsang pembaca untuk merenungkan hakikat kehidupan manusia sesungguhnya sehingga bisa menumbuhkan wawasan dan pandangan baru bagi pembaca dalam menghadapi fenomena-fenomena hidup yang muncul ke permukaan. Dengan demikian, batin pembaca akan diwarnai oleh berbagai ragam pengalaman yang majemuk yang melingkupi sosok kehidupan manusia.
Publik
Ada semacam kepuasan batin ketika publik berhadapan dengan sebuah cerita rekaan yang sarat dengan nilai-nilai susastra. Tanpa disadari, batin pembaca akan tersaluri oleh idiom-idiom falsafi yang mengungkap makna kearifan hidup, analisis watak manusia secara psikologis, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ragam sosial budaya yang melingkupi paguyuban masyarakat secara komunal, renungan-renungan religius, dan sebagainya.
Unsur-unsur multidisipliner ini akhirnya membuat mata batin pembaca menjadi tajam, khazanah batinnya semakin kaya akan berbagai ragam kehidupan manusia yang berkutat dengan segala macam persoalan yang dihadapi pada masa lampau, masa kini, atau masa yang akan datang.dari uraian di atas dapat kita tarik semacam garis kesimpulan bahwasanya dengan banyak membaca cerita rekaan yang berbobot sastra, batin pembaca semakin kaya, terisi oleh pengalaman-pengalaman baru yang unik yang sulit diperoleh dari realitas yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. *** (Sawali Tuhusetya)
Sastra Koran versus Sastra Cyber
Semenjak dunia sastra merambah dunia maya alias internet, banyak kalangan –terutama mereka yang mengklaim dirinya sebagai sastrawan– merasa gerah. Pasalnya, lewat berbagai blog yang gratisan, hampir setiap orang bisa memublikasikan teks-teks sastra ciptaannya. Bahkan, teks sastra yang tergolong “sampah” pun bisa dengan mudah terpublikasikan. Hal yang (hampir) mustahil terjadi dalam sastra koran. Untuk bisa meloloskan teks sastranya di sebuah media cetak, minimal harus lolos dari “barikade” selera sang redaktur. Ini artinya, tidak bisa sembarang teks sastra bisa lolos dari persyaratan ketat yang ditetapkan oleh sang redaktur.
Menurut hemat saya, dikotomi sastra koran versus sastra cyber bukanlah perkara substansial. Sastra sangat erat kaitanya dengan dunia imajiner yang bebas ditafsirkan oleh orang dari berbagai kalangan. Ini artinya, siapa pun punya hak untuk menafsirkan nilai-nilai estetika dan nilai-nilai etika alias pesan moral yang terkandung di dalamnya. Persoalan sastra koran dan sastra cyber hanyalah persoalan medianya saja. Kalau sastra koran selalu mengenal batasan-batasan yang dikendalikan oleh otoritas sang redaksi dan selera pasar, sastra cyber (hampir) tak mengenal batasan-batasan otoritas itu. Setiap orang pun bebas memiliki blog gratisan yang bisa dijadikan sebagai media untuk memublikasikan karya-karyanya. Selain itu, koran juga mengenal batasan dimensi ruang dan waktu. Pembacanya hanya kebetulan mereka yang berlangganan dan dibatasi oleh waktu penerbitan. Untuk rubrik sastra dan budaya biasanya terbit setiap hari Minggu yang acapkali hanya dijadikan sebagai “suplemen” hiburan, melengkapi kolom-kolom keluarga dan entertainment lainnya.
Catatan dari Balik Kabut
Dari balik kabut
Kurentangkan tangan dhaifku menggapai mega-mega
Kutuliskan namaku di setiap labirin kesunyian
Memberikan tanda-tanda
Aku berdiri di sini
Di balik kabut mega-mega
Kusaksikan para malaikat mengadili para pendosa
Pilu tangis mengiris kolong langit
Menggetarkan semesta
Kabut berwarna merah darah
Mengurung semesta
Namaku tak lagi punya tanda
***
Ya, negeri ini memang tengah diselimuti kabut. Tak hanya tsunami, bencana alam, atau kebakaran hutan. Tapi ada yang jauh lebih parah yang telah membikin negeri terpuruk dalam lumpur kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. Ya, korupsi! Maksiat korupsi telah membikin bangsa ini jatuh dalam kebangkrutan. Marwah dan martabat bangsa tergadaikan oleh keserakahan sekelompok elite yang telah melupakan sumpah dan ikrarnya. Demikian parahnya “efek domino” yang ditimpakan oleh para koruptor sampai-sampai bangsa dan negeri ini tak berdaya ketika bangsa lain melempari wajah bangsa kita dengan telor busuk. Bangsa kita yang miskin, terbelakang, dan bodoh seakan-akan sudah tak punya kekuatan untuk sekadar mengingatkan, apalagi berteriak. Sipadan dan Lipadan sudah diembat, batik sudah diklaim sebagai karyanya, lagu-lagu sudah disikat habis dan dipatenkan. Belum lagi terhitung saudara-saudara kita yang menjadi korban arogansi bangsa yang mengaku dirinya sebagai bangsa serumpun itu. Namun, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mengerutkan jidat dan menunggu-nunggu, ulah apalagi yang akan dipertontonkan oleh negeri jiran itu di depan mata kita.
 Kebangkrutan bangsa kita agaknya sedang dijadikan “amunisi” negeri jiran itu untuk mengumbar arogansi dan kejumawaannya. Mereka punya nyali karena mereka yakin kita tak akan sanggup melawannya. Tak heran jika kasus pemukulan wasit karate Indonesia oleh polisi Malaysia pun hanya dianggap sebagai perkara kecil yang tak perlu diladeni. Kekerasan terbuka yang dilakukan oleh pasukan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) terhadap imigran Indonesia telah menjadi bagian “hiburan” dari preman-preman yang didesain secara resmi oleh negeri itu.
Kebangkrutan bangsa kita agaknya sedang dijadikan “amunisi” negeri jiran itu untuk mengumbar arogansi dan kejumawaannya. Mereka punya nyali karena mereka yakin kita tak akan sanggup melawannya. Tak heran jika kasus pemukulan wasit karate Indonesia oleh polisi Malaysia pun hanya dianggap sebagai perkara kecil yang tak perlu diladeni. Kekerasan terbuka yang dilakukan oleh pasukan Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) terhadap imigran Indonesia telah menjadi bagian “hiburan” dari preman-preman yang didesain secara resmi oleh negeri itu.
Teks Sastra Tak Pernah Tercipta dalam Situasi yang Kosong
Meski hanya sebatas lomba penulisan cerpen dalam level kabupaten, setidaknya mereka bisa menyuarakan bagaimana mereka berproses kreatif. Hal ini juga semakin menguatkan adanya sebuah opini bahwa (hampir) tak ada cerpen yang dibuat semata-mata hanya menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide. Sekecil apa pun, ada fenomena sosial-budaya yang menggelisahkan batin sang penulis sehingga tergoda untuk menyajikannya ke dalam sebuah cerpen.
 Ya, ya, ya, tiba-tiba saja saya jadi ingat A. Teeuw yang pernah menyatakan bahwa teks sastra (termasuk cerpen) tak akan pernah tercipta dalam situasi yang kosong. Artinya, ada kode bahasa, sastra, dan budaya yang senantiasa dilibatkan, baik disadari maupun tidak, oleh pengarang dalam teks-teks sastra yang diluncurkannya. Meski hanya sebatas peserta lomba penulisan cerpen dalam lingkup kabupaten, tetapi kreativitas mereka bisa memberikan gambaran umum bagaimana seorang pengarang berproses kreatif.
Ya, ya, ya, tiba-tiba saja saya jadi ingat A. Teeuw yang pernah menyatakan bahwa teks sastra (termasuk cerpen) tak akan pernah tercipta dalam situasi yang kosong. Artinya, ada kode bahasa, sastra, dan budaya yang senantiasa dilibatkan, baik disadari maupun tidak, oleh pengarang dalam teks-teks sastra yang diluncurkannya. Meski hanya sebatas peserta lomba penulisan cerpen dalam lingkup kabupaten, tetapi kreativitas mereka bisa memberikan gambaran umum bagaimana seorang pengarang berproses kreatif.Karya-karya Pramudya Ananta Toer, Umar Kayam, Rama Mangun Wijaya, atau Ahmad Tohari –sekadar untuk menyebut beberapa nama—adalah beberapa contoh teks sastra yang memanfaatkan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai sebagai sumber pengembangan ide. Karya-karya mereka tidak semata-mata “memberhalakan” imajinasi, tetapi juga memasukkan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai kearifan lokal hingga menjadi sebuah teks sastra yang indah dan eksotis.
Bumi Manusia, yang merupakan salah satu dari tetralogi Buru karya Pram, misalnya, tak lepas dari konteks sosial-budaya yang terjadi ketika Pram mengalami masa-masa represif. Melalui kekayaan imajinasi dan intuisinya, Pram berhasil mengangkat persoalan sosial-budaya yang terjadi antara tahun 1898 hingga tahun 1918, ketika muncul pemikiran politik etis dan masa awal periode Kebangkitan Nasional. Masa-masa yang memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran nasionalisme di Indonesia pada awal pergerakan nasional.
Karya-karya Umar Kayam, agaknya juga banyak membidik persoalan sosial budaya sebagai bagian esensial dari teks sastra yang diciptakannya. Dalam cerpen “Sri Sumarah” dan “Bawuk”, atau dalam novel Para Priyayi, misalnya, Umar Kayam tampak sangat dipengaruhi oleh latar sosio-kultural etnik Jawa. Tokoh-tokoh semacam Tun, Bawuk, maupun Hari agaknya dijadikan sebagai figur yang “mewakili” orang-orang Jawa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan kehidupan.
Burung-Burung Manyar karya YB Mangunwijaya pun setali tiga uang. Dengan mengangkat kisah seputar dunia revolusi Indonesia antara tahun 1934 hingga 1950, Rama Mangun berupaya mengetengahkan peristiwa yang sarat konflik antara orang Indonesia sendiri dan para meneer Belanda atau antar-orang Indonesia yang anti Republik. Novel yang dinilai HB Jassin bernada humoristis, kadang-kadang tajam mengiris, penuh pengalaman dahsyat, keras dan kasar, tapi juga romantik penuh kelembutan dan kemesraan ini juga tak lepas dari persoalan sosial-budaya yang berusaha menggambarkan sisi-sisi kemanusiaan dari pribadi-pribadi yang memiliki idealisme berbeda, terutama dalam hubungannya dengan pengertian nasionalisme pada konteks Indonesia saat itu.
Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari yang disebut-sebut banyak pengamat sebagai puncak pencapaian sastra pengarang asal Banyumas, Jawa Tengah ini, memotret sebuah masa ketika Indonesia memasuki zaman gelap politik 1965. Novel terasa amat kuat jalinan konflik sosial-budayanya yang beragam, huru-hara politik, hilangnya sebuah tradisi, atau terdesaknya kehidupan desa.
Dalam konteks demikian, tak berlebihan kalau Ayu Utami pernah menyatakan bahwa sebuah karya sastra tak dapat dilepaskan dari konteks sosial di mana ia dilahirkan. Lebih lanjut, pengarang novel Saman itu menyatakan bahwa sastra hadir sebagai bentuk penyikapan terhadap kehidupan sehari-hari, dan tak jarang sastra muncul sebagai perlawanan terhadap keadaan. ***












 Blog ini merupakan kumpulan catatan tentang dunia bahasa dan sastra Indonesia. Didedikasikan buat para peminat masalah kebahasaan dan kesastraan sebagai bagian dari budaya dan karakter bangsa.
Blog ini merupakan kumpulan catatan tentang dunia bahasa dan sastra Indonesia. Didedikasikan buat para peminat masalah kebahasaan dan kesastraan sebagai bagian dari budaya dan karakter bangsa.